 Ahok.Org (06/03) – Komisi II DPR RI terus melakukan penggalian informasi, data dan masukan dari para pakar terkait dengan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ahok.Org (06/03) – Komisi II DPR RI terus melakukan penggalian informasi, data dan masukan dari para pakar terkait dengan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tanggal 1 Maret 2011 Komisi II DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengu Buwono X yang dihadiri pula oleh Wakil Gubernur Sri Paku Alam IX.
Sri Sultan menjelaskan bahwa kelahiran DIYdapat ditelusuri dari latar belakang sejarahnya, yaitu sebelum Belanda menancapkan kekuasaannya di Jawa, Kerajaan Mataram Islam di bawah Sultan Agung pada tahun 1613-1646 berkuasa atas Jawa kecuali Banten dan Batavia, Madura dan Sukadana (Kalimantan Barat), Belanda mengakui kedaulatan Kerajaan Mataran sehingga harus membuat politik kontrak selama Belanda di tanah Jawa. Menjelang Mataram Islam bertekuk lutut kepada Belanda pada masa Paku Buwono II, Pangeran Mangkubumi memberontak sampai akhirnya terjadi Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang kemudian membagi dua kerajaan Mataram yang selanjutnya dikenal dengan ”palihan negari”. Pangeran Mangkubumi memperoleh sebagian wilayah yang kemudian dibangun menjadi Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat.
Selanjutnya ketika Inggris mengambil alih kekuasaan dari penjajahan Belanda, lahirlah sebuah kerajaan baru Kadipaten Pakualaman, yang wilayahnya diambil dari sebagian Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, dan diberikan kepada Pangeran Notokusumo yang selanjutnya bergelar Pangeran Adipati Ario Paku Alam I.
Pada jaman pendudukan Jepang, eksistensi Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman diakui oleh Jepang, oleh karenanya ketika Jepang pergi, kedua kerajaan tersebut telah siap menjadi sebuah negara sendiri, lengkap dengan sistem pemerintahannya (susunan asli), wilayah dan penduduknya.
Selanjutnya Sultan menjelaskan bahwa pada saat mendengar berita Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 kemudian mengirim surat kawat kepada Presiden Soekarno yang berisi ucapan selamat dan sikap politik untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Selanjutnya sikap politik tersebut dibalas dengan perlakuan istimewa dari Presiden Soekarno berupa pemberian Piagam Penetapan tertanggal 19 Agustus 1945. yang intinya Presiden Soekarno menetapkan Sri Sultan dan Sri Paku Alam tetap pada kedudukannya dengan kepercayaan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan Daerah Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia.
Selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengeluarkan amanat yang kemudian dikenal sebagai amanat 5 September 1945 yang isinya antara lain: Pertama, memerintahkan kepada segenap penduduk Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pakualaman menjadi bagian Republik Indonesia. Kedua, segala urusan pemerintahan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pakualaman di tangan Hamengku Buwono IX. Ketiga, hubungan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pakualaman dengan pemerintah pusat bersifat langsung dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.
”Dalam perkembangannya willayah Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pakualaman menjelma menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya diatur di dalam UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peristiwa sejarah tersebut yang melandasi pengakuan hukum atas DIY, dan fakta berikutnya dengan berbagai pertimbangan Yogyakarta ditetapkan menjadi Ibu kota Republik Indonesia dari tahun 1946-1949” demikian Sultan.
Sri Sultan juga mengatakan bahwa mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY yang telah berjalan selama ini konstitusional, hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 18B UUD 1945. Pasal ini dimaksudkan untuk mengakomodir daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa, sperti Aceh, DKI Jakarta, DIY dan Papua (lex specialist). Sementara Pasal 18 ayat (4), dimaksudkan untuk mengatur daerah-daerah lainnya (lex generalist). Menurut Sultan, mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang demikian berdasarkan teori hukum merupakan hak konstitusional bersyarat (fundamental rights of constitusional condition), artinya sepanjang tidak menyalahi konstitusi dan sepanjang masih berlaku dan mendapatkan dukungan atas luas dari masyarakatnya maka proses yang demikian konstitusional.
Sultan berpendapat bahwa pandangan demokrasi di Indonesia telah terwadahi dalam Sila Keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lebih lanjut Sultan mengatakan saat ini ada semacam hegemony of meaning yang mendefinisikan bahwa satu-satunya metode rekruitment yang demokratis hanya melalui pemilihan secara langsung. Euphoria pemilihan telah meminggirkan kekhasan demokrasi Indonesia yang berbasis pada prinsip kekeluargaan. Wajah demokrasi Indonesia serta-merta bermetamorfosa menjadi westernistik.
”Demokrasi sebenarnya merupakan dimensi humanitas atau kebudayaan, karenanya demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu hasil kreativitas manusia yang berkebudayaan dan berkeadaban. Sementara konsepsi demokrasi sendiri dari waktu ke waktu telah mengalami perubahan, seperti welfare democracy, people’s democracy, social democracy, participatory democracy, dan sebagainya. Puncak demokrasi yang yang paling diidealkan pada akhirnya adalah demokrasi yang berdasar atas hukum atau constitusional democracy. Dalam perspektif ini, demokrasi terwujud secara formal dalam mekanisme kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan kenegaraan. Sedangkan secara substansial demokrasi memuat nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang terwujud dalam perilaku budaya masyarakat setempat”, demikian Sultan.
Gubernur DIY tersebut menjelaskan pula bahwa apabila mengacu kepada konsepsi constitusional democracy, maka DIY telah diatur di dalam Pasal 18B UUD 1945, dan juga telah diatur di dalam Pasal 91 huruf b UU No. 5 Tahun 1974 yang mengamanatkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DIY, tidak terikat pada ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, selanjutnya Pasal 122 UU No. 22 Tahun 1999 dan Pasal 226 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1974 adalah tetap.
Oleh karena itu Sri Sultan Hamengku Buwono X berpesan agar pengakuan keistimewaan DIY tetap dipertahankan, tidak saja merupakan keniscayaan sejarah dan konstitusi melainkan juga fakta sosiologis yang sampai sekarang masih didukung oleh sebagian besar masyarakat Yogyakarta, dan masyarakat secara luas. Tidak ada keraguan bahwa persoalan mendesak yang dibutuhkan masyarakat DIY saat ini adalah instrumen hukum yang legitimate untuk mengakui (recognition principle) dan menghormati (respectition) Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sri Sultan mengusulkan agar judul RUU tentang Keistimewaan Provinsi DIY diubah menjadi RUU tentang Daerah Istimewa Yogyakarta atau RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasannya tidak merujuk pada original intent bunyi Pasal 18B ayat (1), juga tidak sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY yang secara eksplisit menyebutkan ”setingkat provinsi” yang dapat diartikan tidak sama dengan provinsi, sekaligus sebagai pembeda dengan daerah lainnya yang diberlakukan ketentuan hukum yang bersifat umum (lex generalis).
Ada beberapa fakta sejarah yang dikemukakan oleh Pakar Sejarah Prof. Dr. Djoko Suryo terkait dengan DIY ketika menjadi nara sumber di Komisi II DPR RI tanggal 2 Maret 2011 lalu. Prof. Joko mengemukakan bahwa DIY pernah menjadi Kota Revolusi atau Kota Perjuangan tahun 1945-1949 dan menjadi Ibu Kota Republik Indonesia pada tahun 1946-1949. Di samping itu Yogyakarta menjadi penyelamat dan jembatan emas dalam perjuangan Republik Indonesia mencapai kemenangan dan pengakuan kedaulatan Negara RI oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dan dunia internasional. Kemenangan perjuangan tersebut telah dapat mewujudkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan sejak berakhirnya perang kemerdekaan tahun 1945 – 1949. Keberhasilan ini dicapai melalui perjiuangan fisik (militer) dan non fisik (diplomasi) yang semuanya dilakukan melalui kendali perjuangan dari Yogyakarta.
Dikatakan bahwa Kota Yogyakarta ketika menjadi Ibukota RI telah bertanggung jawab menjadi benteng Republik Indonesia, terbukti selain menjadi ajang perang diplomasi, juga menjadi ajang perang fisik berupa pertempuran dalam menghadapi Agresi Belanda II yang sangat menentukan terhadap keselamatan Republik Indonesia. Sebagaimana dimaklumi bahwa pada tanggal 19 Desember 1948 Yogyakarta diserbu dan diduduki tentara Belanda. Soekarno, Hatta dan Agus Salim (Menlu) dan sebagian anggota kabinet ditangkap dan diasingkan ke Brastagi dan Bangka, Pemerintahan Darurat RI dipindahkan ke Bukit Tinggi (PDRI). Pertempuran demi pertempuran meletus, dan salah satu diantaranya adalah pertempuran 6 jam di Yogyakarta pada 1 Maret 1949, yang kemudian menjadi salah satu tonggak Sejarah Perjuangan RI yang penting.
Lebih lanjut Joko berpendapat bahwa melekatnya jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan kedudukan Sri Sultan dan Sri Paku Alam selama ini mengisyaratkan sebagai perpaduan melekatnya bentuk kepemimpinan legal rasional (rational-legal authority) yang berlaku pada jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan bentuk kepemimpinan kultual (traditional authority) yang berlaku pada kedudukan Sultan dan Sri Paku Alam. Bentuk pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut telah berlangsung sejak awal 1945 hingga masa kini, telah berjalan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku tanpa mengalami hambatan suatu apapun. Hal ini membuktikan bahwa bentuk pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut sejak lama telah diterima dan didukung oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurut Djoko Suryo, berpangkal dari realitas empiris tersebut maka dapat dipahami apabila aspirasi masyarakat DIY pada masa kini tetap menghendaki tidak adanya perubahan bentuk pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang melekat dengan kedudukan Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam yang bertahta sebagaimana yang telah berlangsung pada masa-masa sebelumnya.
Prof. Djoko Suryo menjelaskan pula bahwa, ada beberapa alasan yang mendasari kelekatan jabatan kepemimpinan legal-rasional dan kedudukan kepemimpinan kultural tersebut di atas tidak bertentangan, dan sebaliknya malahan bersinergi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan mewujud menjadi pelayanan publik secara efektif, produktif dan akseptabel bagi rakyat dan masyarakat DIY, yaitu: Pertama, secara historis faktual bahwa sejak bergabungnya Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro Pakualaman bergabung menjadi bagian Negara Republik Indonesia, kedudukan Sultan sebagai raja yang memegang kekuasaan politik negara kerajaan secara penuh (Monarch), telah bergeser menjadi raja kultural, yaitu sebagai raja pemegang simbol budaya Kraton Yogyakarta yang lingkup wilayahnya terbatas hanya pada Cepuri Kraton. Sebagai pemegang simbol budaya Kraton Yogyakarta, Ia masih diterima sebagai pemimpin budaya Jawa yang berfungsi sebagai panutan, pelindung, pengayom, penjaga ketentraman dan kedamaian kehidupan moral/spiritual dan relegiusitas masyarakat DIY.
Kedua, dalam kedudukannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Sultan dan Sri Paku Alam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam pemerintahan RI, termasuk harus mengangkat sumpah jabatan. Hal ini berarti bahwa Sultan dan Sri Paku Alam memiliki tanggung jawab yang sama di muka hukum. Ketiga, pengangkatan dan penetapan kedudukan Sultan Sri Paku Alam sebagai raja kultural telah diatur oleh paugeran atau pranatan yang berlaku dalam internal masing-masing kraton dan kadipaten. Paugeran kraton telah merumuskan segi-segi penting yang berkaitan dengan filosifi/pandangan dunia tentang negara (kerajaan), konsep raja, kedudukan raja dan syarat-syarat menjadi raja yang ideal.
”Konsep tentang raja dan kekuasaan Kraton Yogyakarta sesungguhnya tercermin di dalam gelar raja Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati ing Ngalaga, Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Gelar ini merupaka simbol dan repsentasi filosofis kerangka konseptual tentang raja, kerajaan, dan keilahian dalam pandangan Islam Jawa. Kata Hamengku Buwono menandai simbol dan otoritas raja yang bertugas untuk melindungi jagad. Kata ini memuat 3 (tiga) pokok makna, yaitu Hamengku, Hamangku, dan Hamengkoni. Hamengku mengandung makna kewajiban raja untuk melindungi setiap orang tidak pandang kedudukan sosialnya, termasuk mereka yang tidak menyukainya. Hamangku bermakna kepemimpinan yang meletakkan kepentingan rakyat di atas kepentingan dirinya dengan sikap suka memberi daripada meminta, dan Hamengkoni merujuk pada peningkatan kekuatan untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat di jalan Allah”, demikian Djoko.
Keistimewaan Yogyakarta tidak terlepas dari Sultan dan Sri Paku Alam. Jadi keistimewaan DIY terletak pada daerahnya dan juga Sultannya. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Sekarang yang dipikirkan adalah bukan memarkir Sri Sultan dan Sri Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Utama, tetapi dicarikan formulasi jabatan yang sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu bisa juga Sultan sebagai Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai Piagam Penetapan tanggal 19 Agustus 1945 dan Amanat 5 September 1945. Atau pejabat ”setingkat provinsi” seperti amanat UU No. 3 Tahun 1950. Jadi tidak harus gubernur. Jadi intinya jangan sampai RUU ini memberangus, mengaburkan, apalagi menghilangkan jejak sejarah bangsa ini. Piagam Penetapan 19 Agustus 1945 dan Amanat 5 September 1945 tersebut harus dipahami sebagai ”wasiat sejarah” yang harus dipatuhi dan dihargai oleh setiap anak bangsa, apapun statusnya, kapan. dan dimana pun juga.
Peneliti Utama LIPI Dr. R. Siti Zuhro, PhD dalam Makalah: DIY Dalam Konteks NKRI, Otda dan Demokrasi (3/3/2011) mengatakan bahwa dalam Piagam Penetapan yang diberikan Presiden Soekarno pada tanggal 19 Agustus 1945, dengan tegas menetapkan Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Abdurachman Sayidin Panatagama Kalifatullah Ingkang Kaping IX dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam Ingkang Kaping VIII pada kedudukannya. bergabungnya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan amanat Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII tanggal 5 September 1945 dan 30 Oktober 1945, merupakan bukti dan menjadi fakta sejarah yang menunjukkan kuatnya komitmen rakyat dan pimpinan di Yogyakarta dalam berjuang menegakkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Siti Zuhro menilai bahwa pemerintah tampak tidak konsisten dan justru menciptakan supremasi lambang yang mereduksi demokrasi karena pembuatan Perdais harus mendapat persetujuan Gubernur Utama. RUU DIY perlu dirumuskan secara konsisten, demokratis, tidak membingungkan dan aplikatif. Jangan sampai ada standar ganda dalam perumusan RUU DIY. Untuk itu, harus ada peraturan yang jelas dan tegas yang disebutkan secara eksplisit bahwa RUU DIY memberikan kewenangan dan urusan sesuai dengan Konstitusi dan NKRI serta pendanaan dari negara. Perlu pemisahan antara istilah kepala negara dan kepala pemerintahan atau dalam konteks lokal di Indonesia, bisa disebut kepala daerah dan kepala pemerintahan. Dengan pemilahan ini akan lebih jelas siapa melakukan apa dan siapa bertanggungjawab apa. Rumusan RUU K DIY saat ini sangat rancu dan tidak cukup tegas memisahkan kewenangan tersebut, sehingga terkesan seolah-olah Sri Sultan perlu merangkap jabatan (sebagai kepala daerah dan kepala pemerintahan). Dalam sistem pemerintahan presidensiil, Presiden memiliki kewenangan dan otoritas penuh menata daerah dan mengelolanya serta bertanggunjawab atas kemajuan dan kegagalan yang dialami daerah. Oleh karena itu, dalam konteks menata daerah-daerah, perlu mengakomodasi suara mereka dan menyesuaikan dengan perkembangan kekinian Indonesia, meskipun ini bukan berarti mereduksi kekhasan/karakteristik atau pluralitas lokal yang dimiliki daerah.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Para pemimpin bangsa ini, siapa pun dia, wajib hukumnya untuk meghargai dan menghormati sejarah yang telah diletakan para pendiri bangsa ini tanpa kecuali. Yogyakarta merupakan bagian terbesar dari sejarah bangsa ini, terutama perannya pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, dimana banyak terjadi pergolakan neo kolonialisme. Di tengah badai besar tersebut, Yogyakarta tampil sebagai benteng terakhir pertahanan bangsa ini. Yogyakarta ibaratnya ”lilin kecil”yang menerangi jalan perjuangan bangsa ini untuk mempertahankan NKRI dari cengkraman penjajahan kolonial. Apakah jasa Yogyakarta harus dikubur atau dilupakan begitu saja karena (nafsu) kepentingan politik sesaat?
Pesan Soekarno: ”Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah” atau yang sering dikenal dengan istilah ”JASMERAH”. Pesan ini tentu beralasan. Sebab generasi penerus bangsa ini bisa saja ”lupa diri” ketika memimpin bangsanya. Pemimpin yang melupakan sejarah (perjuangan) bangsanya adalah pemimpin yang “lalim dan ceroboh”. (Kamillus Elu, SH).
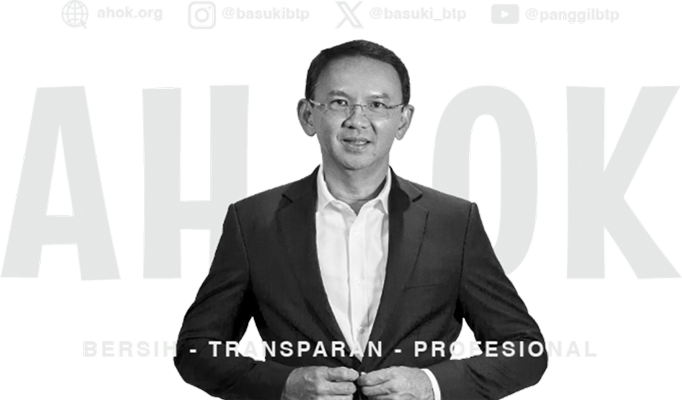


Jogjakarta udah aman dan tenteram mengapa harus di utak atik?Harus bisa membedakan antara demokrasi dan keistimewaan Jogja. JASMERAH.Jangan melupakan sejarah.Tepat sekali apa yang dikatakan Bung Karno founding father bangsa Indonesia